Saat Terakhir
Duar. Kilat menyambar. Dahyat. Memekakkan telinga. Langit malam meruntuhkan air. Ya! Buncahan hujan deras menghantam bumi. Teramat sangat malah. Membuat jalanan banjir. Angin malam berkesiur kencang. Dingin membeku. Awan hitam mendominasi. Kelam. Gemintang indah tertutup. Terhalang. Gemerlap lampu-lampu musnah sudah. Ibu Kota ini memang benar-benar layaknya zaman batu. Gelap. Hanya sesekali cahaya kilat membuat terang. Sekejap.Apa yang sebenarnya diinginkan takdir langit pada malam ini? Entahlah. Tak ada yang tahu. Apa pula yang sedang terjadi? Entahlah. Di kamar yang serba putih, Dimas meratap. Ya! Yang ia mampu perbuat sekarang hanyalah meratap. Diam seribu bahasa. Melihat Dewi terbaring lemah. Tak berdaya. Wajahnya pucat bagai seorang mayat. Tapi ia masih bernafas. Selang-selang menghujam tubuhnya yang semakin ringkih dan ringkih. Matanya sayu masih setengah membuka. Mencoba mengutarakan isi hati. Entahlah. Benar-benar tak karuan malam ini. Beribu-ribu kilat terus menyambar. Membawa pedih. Sama seperti hatinya sekarang. Berbagai sesal menghantui tiap detik beku di kamar ini. Dokter memvonis bahwa usia Dewi tak akan lama lagi. Tinggal menghitung hari saja. Kankernya sudah menjalar-jalar ke seluruh tubuh. Stadium 4. Sangat parah. Dan di kamar yang serba putih ini, mungkin ajal akan menjemputnya. Entahlah. Dimas hanya mampu meratap. Terus menerus. Perasaannya bercampur aduk antara amarah dan sesal. Rasanya ingin sekali ia mencabik-cabik mulut dokter bajingan itu. DOKTER SOK TUHAN!!! Berani-beraninya ia membatasi umur manusia. DOKTER LAKNAT. DOKTER B-A-J-I-N-G-A-N. Batinnya berteriak parau. Memilukan.
Di kamar yang serba putih ini, Dewi kian kalang kabut dengan sakit yang dideritanya. Menangis basah. Menahan sakit. Namun, tak kuasa membrontak. Ia sudah lemas. Tak berdaya. Matanya sayu masih membuka. Menghipnotis Dimas yang melihatnya iba.
“APAKAH AKU CANTIK?”
“Dimas…” Dewi berteriak. Berlari terpongah-pongah ke arah Dimas yang berada di seberang jalan. “Tunggu aku…” Apa yang ada di benak perempuan itu sebenarnya. Berlari tanpa melihat arah. Menyeberang jalan seenaknya saja. Untunglah jalanan senggang.
Dimas menghentikan langkah. Terpaku sejenak. Menunggu Dewi yang masih berlari tak peduli arah. Tak lama, ia sudah di hadapan. Nafasnya ngos-ngosan. Sedikit tetes peluh di dahi menyembul.
“Berangkat ke kampusnya bareng yaa.” Ia tersenyum. Lesung di pipi menambah menawan. Sungguh ayunya. Dimas tak kuasa menatap lamat-lamat wajah cantik itu. Jantungnya terasa sangat berderap jika di dekatnya. Apalagi jika senyuman itu terhias. Bagai sedang di kutub, badannya langsung membeku tak berkutik. Salah tingkah. Tapi, ada tanda tanya besar dalam hatinya. Dewi, seorang anak direktur perusahaan ternama, kaya raya, mobil melimpah, kenapa malah memilih berangkat ke kampus bersama Dimas, laki-laki kere yang hidup ngekos di tengah hamparan apartemen Ibu kota, berangkat dengan naik metro mini yang asapnya macam rumah kebakaran. Bukankah ia punya banyak mobil ber-AC yang adem dan mulus? Inilah yang membuat bingung Dimas selama beberapa bulan terakhir setelah mengenalnya.
Ya! Sudah tiga bulan ini mereka menjalin pertemanan. Hanya sebatas teman. Dan apakah mereka juga menginginkan hubungan itu hanya sebatas teman saja? Entahlah. Dimas, sudah lama ia memendam rasa kepada Dewi. Tapi, ia tahu diri. Minder. Seorang anak orang rendahan mana mungkin bisa menjadi kekasih seorang anak direktur yang kaya raya, cantik pula. Benar-benar bagai punuk merindukan bulan. Mungkin tidak! Bagaikan punuk merindukan Neptunus, planet terjauh di tata surya. Dan itu menandakan kalau hubungan mereka tak akan pernah terjadi. Tidak pernah terbesit dalam hati Dimas kalau ia akan menjalin hubungan dengan Dewi sebagai seorang kekasih, melamarnya, menikahinya, mempunyai anak bersamanya, mempunyai cucu dari anak-anak mereka dan hingga akhirnya mati bersama dalam pelukan cinta antara seorang kakek dan nenek. Tak pernah terbesit pikiran seperti itu dalam diri Dimas. Setiap kali ia membayangkan bagaimana menjalin hubungan kekasih dengannya, di saat itu pula ia selalu mengandaskan pikirannya dalam-dalam. Tak mungkin anak seorang direktur kaya mau dengan laki-laki kere. Dan karena itulah ia selalu memendam rasa. Hingga saat ini pun ia masih memendamnya. Tak mau diungkapkan. Ia terlalu malu untuk mengungkapnya. Ia hanya LAKI-LAKI KERE YANG NGEKOS DI ANTARA HAMPARAN APARTEMEN IBU KOTA.
“Hai, kok melamun.” Dewi menggertak kecil. Mengagetkan Dimas. Melempar senyum yang manis itu.
“Oh, iya…” Dimas memalingkan muka. Salah tingkah. Menatap Dewi. Sebentar. Ia tak kuasa menatap Dewi lamat-lamat. Apalagi menatap mata beningnya yang memesona. Ia benar-benar tak kuasa “Kenapa, Dew?”
“Kita berangkat ke kampusnya bareng yaa.” Ia kembali meminta untuk yang kedua kalinya.
Dimas membuang jauh-jauh tanda tanya besar itu. Juga pendaman cintanya. Mungkin saja Dewi ini adalah seorang anak yang merakyat. Tak sombong. Mau bergaul dengan siapa saja walaupun orang itu adalah orang yang kere. Dan ia melakukan ini bukan karena adanya cinta yang terbelit di hatinya juga. Dimas yakin kalau Dewi tidak melakukannya karena diam-diam ia juga mencintai Dimas. Mana mungkin anak seorang direktur cinta dengan laki-laki kere. MUSTAHIL
“Iyaa. Ayo berangkat.”
Whong… Sebuah metro mini melintas. Deru knalpotnya membuat bising. Pun asapnya. Menutup muka Dewi yang putih mengkilap bagai mutiara. Dan kini muka itu ternoda dengan asap hitam polusi. Kalau begini laki-laki mana yang tak tega kala melihat seorang perempuan begitu tersiksa dengan asap itu. Apalagi cantik pula. Dan semua ini masih menjadi teka-teki dalam diri Dimas. Kenapa seorang anak direktur kaya yang punya banyak mobil ber-AC dan mulus malah lebih memilih naik metro mini bising dan penuh kebul?
Di perjalanan, mereka hanya mengobrol sesuatu yang sama yang selalu mereka bicarakan tiap hari. Dewi selalu bercerita pada Dimas dengan apa-apa yang terjadi dengannya. Seakan-akan Dimas itu adalah diary curahan hatinya. Semuanya tercurah ke dalam telinga Dimas. Tanpa satupun yang terlewat.
“Hai, Dim. Kau tahu, sebenarnya aku sedang suka dengan seseorang.” Dewi menggumam.
Mendengar itu Dimas terperangah. Hatinya bergejolak. Oh Tuhan, siapakah yang dicintainya? Ia ragu. Tak mungkin Dewi mencintai dirinya yang kere dan rendahan.
“Oh, iya? Benarkah? Siapa?” Tanya Dimas. Melempar senyum walau itu hanya sebatas senyum palsu.
“Cie, yang kepo cie…” Dewi tersenyum manis. Merasa pancingannya berhasil membuat Dimas bertanya-tanya.
Pipi Dimas memerah. Padahal ia mejawab itu karena tak enak dengan sikap Dewi yang sering curhat dengannya. Jika reaksinya datar-datar saja, mungkin Dewi tak akan tersenyum seperti itu. Ia tak tega. Ia selalu ingin melihat senyum Dewi yang memesona. Tapi, pipi Dimas benar-benar memerah kali ini. Apakah ini sebuah tanda? Apakah pertanyaan itu bukan sebuah tanya akting belaka? Dan apakah senyum itu bukan senyum palsu yang sesungguhnya? Entahlah.
“Kamu mau tau nggak siapa?” Dewi bersuara. Tersenyum indah. Memesona.
“Emang siapa?” Tanya Dimas. Memasang wajah berpura-pura ingin tahu sekali. Walau mungkin wajahnya tidak dibuat-buat. Ia memang benar-benar ingin mengetahuinya.
“Tuh,” jawab Dewi sambil menunjuk ke suatu arah. Telunjuknya menuding ke sopir bus mini yang sudah tua. Kumis tebal. Wajah glopot dan berslampir handuk kecil di lehernya.
“Sialan. Kamu itu sukanya bercanda.” Dimas kesal. Merasa tertipu. Mencubit pipi Dewi yang lembut. Ia tersenyum. Lesung pipinya membuat hati berbunga-bunga. Anak-anak rambut yang menutup dahi ikut bergoyang. Benar-benar cantik sekali.
“Ih, kamu mah, main cubit-cubit aja. Aku bukan boneka tau.” Dewi bergumam. Membalas cubitan Dimas dengan satu gelitik di pinggang. Mereka bergurau.
Dan entah kenapa, tanpa sadar, mungkin setelah mereka lelah bergurau, Dewi menyandarkan kepalanya pada bahu Dimas. Di tengah riuhnya knalpot bobrok metro mini, ia bagai merasakan sedang berdua saja di suatu alam yang tenang. Milik mereka berdua. Lagi pula, Dimas juga tak keberatan jika bahunya dipinjam perempuan seperti dia. Tapi, hatinya menolak. Apakah ia pantas untuknya? Ia hanya laki-laki kere. Sedangkan Dewi adalah seorang anak direktur perusahaan ternama yang kaya raya.
Tiga bulan berlalu. Dewi dan Dimas kini semakin dekat saja. Tiap hari berangkat kampus bersama. Bercanda di metro sambil selalu menunjuk ke arah supir metro mini yang selalu ganti tiap minggu. Dan Dimas selalu menanggapinya dengan cubitan di pipi Dewi yang selalu membentuk teluk kala ia tersenyum. Atau terkadang juga menjitak kepalanya lembut. Bukan jitakan keras. Mungkin lebih tepatnya membelai. Ya! Dimas kian merasakan perasaannya semakin bergejolak. Tapi, semakin cintanya bergejolak, semakin pula minder itu menguasai dirinya. Lagi-lagi ia berpikir kalau dirinya sama sekali tak pantas mencintai seorang perempuan seperti Dewi. Apalagi kalau Dewi mencintainya. Ia bahkan tak bisa membayangkan bagaimana terpiuhnya hati Dewi jika ia harus hidup berdamping dengan laki-laki kere, miskin seperti dia. Walau ia sebenarnya tahu kalau Dimas hanyalah seorang anak pedagang sayur di desa yang pergi ke Ibu Kota untuk bersekolah. Tapi, bagi Dimas itu sama saja. Ia tak ingin Dewi tersiksa karenanya. Oleh Karena itu, sampai sekarang pun ia belum bisa mengungkapkan perasaan yang diderma batinnya sejak lama. Ia ragu. Teramat sangat malah.
Satu minggu berlalu, di suatu malam yang indah bermilyar gemintang, Dewi mengajak Dimas makan malam bersama. Entahlah. Dimas tak tahu apa maksud makan malam ini. Tapi ia tak enak untuk berkata tidak. Karena itulah ia menyanggupinya. Lama ia menunggu. Satu jam. Dua jam. Tiga jam. Dewi sama sekali tak datang. Dimas mulai punya firasat buruk. Tak pernah sekalipun Dewi mengingkari janjinya. TAK PERNAH. Tapi malam ini, ia tak memegang kata-katanya.
Keesokan harinya, Di suatu pagi hening yang penuh dengan tetesan embun, Dimas merasakan suatu yang berbeda. Pagi itu, sama sekali tak terdengar teriakan Dewi yang lembut memanggil namanya. Menyuruhnya berhenti. Tak ada suara itu. Ia terheran. Ke mana dia? Ke mana panggilan “Dimas…” yang selalu terlontar tiap pagi? Ke mana hentakan kaki buru-buru yang mengejar dirinya? Ke mana kalimat “Berangkat ke kampusnya bareng ya…” Ke mana? Ke mana? Ke mana Dewi sebenarnya?
Dimas menunggu. Mungkin saja Dewi kesiangan. Tapi, sampai satu jam pun ia tak kunjung datang. Akhirnya berangkatlah Dimas seorang diri. Tak ditemani seorang perempuan manis yang selalu menggelitiki pinggangnya. Yang selalu ia cubit pipi teluknya. Di tengah riuhnya dialog orang dan mekakkannya deru knalpot bobrok metro, ia kesepian. Hanya memandang ke luar jendela dengan tatapan kosong yang tak bermakna.
Tiga minggu berlalu. Sudah genap satu bulan Dewi menghilang tanpa sebab sejak ketidakhadirannya di makan malam itu. Dimas semakin bergoncang. Di mana dia? Di mana dia sebenarnya. Ia bertanya pada teman satu kampusnya yang mengambil jurusan sama dengan Dewi mengenai perihal menghilangnya Dewi. Namun, ia tak tahu. Bahkan sudah sebulan juga Dewi tak berangkat ke kampus tanpa memberi surat keterangan satupun. Dan ini membuat Dimas semakin bingung. Di mana Dewi sebanarnya?
Satu minggu lagi berlalu. Setelah mencari-cari keberadaan Dewi, akhirnya segelintir infomasi terkuak juga di telinganya. Pada suatu malam yang terselimut awan mendung yang sangat gelap, salah seorang temannya menelepon. Mengabarkan bahwa DEWI SEDANG SEKARAT.
Kabar itu begitu amat mencengangkan baginya. Dan karena itu, pada malam itu juga, ia hujan-hujanan menuju rumah sakit. Hujan semakin deras membuncah bumi. Disertai dengan kilatan petir dan teriakan guntur. Amat sangat mengerikan. Tapi ia tak peduli. Yang ada di dalam benaknya sekarang adalah Dewi, wanita yang amat sangat dicintainya. S-E-D-A-N-G S-E-K-A-R-A-T.
Hampir tengah malam, ia sampai di rumah sakit. Tubuhnya basah kuyup. Menggigil kedinginan. Tapi ia tak peduli. Orang yang sangat dicintainya sedang sekarat. Terbaring tak berdaya di kamar yang serba putih. Dan ia harus menemuinya.
Setelah melihat Dewi yang sekarang, sungguh dunia bagai sedang diguncang gempa yang sangat dahsyat. Teramat sangat Dimas terperanjat. Matanya terbelalak. Berkali-kali hatinya mengamuk tak percaya. Sungguh. Ia benar-benar tak percaya. Seluruh Dewi yang dikenalnya, kini sudah 180 derajat berubah. Rambutnya yang indah terurai kini sudah tak lagi ada di ubun-ubunya. Ia botak. Wajahnya pucat bagaikan mayat. Tubuhnya ringkih. Teramat sangat malah. Tulang-tulangnya bahkan terukir di kulitnya. Ia sangat kurus. Menyedihkan. Matanya sayu setengah menutup. Tak berdaya. Orangtuanya bilang, kanker telah menggrogotinya banyak tubuh Dewi. Semuanya sudah menjalar-jalar hingga ke organ-organ vital. Dan dokter memvonis kalau umur Dewi tinggal menghitung hari saja. Dan di sela-sela pandangan sayu itu Dewi berucap.
“APAKAH AKU CANTIK?”
Apa maksudnya. Dimas benar-benar tak tahu apa maksud Dewi.
“APAKAH AKU CANTIK?” Dewi bertanya lagi. Suaranya semakin serak dan parau.
“Apa maksumu, Dew?” Dimas bertanya. Tanya yang seharusnya tak ia lontarkan saat itu.
“Kau jawab saja aku, APAKAH MENURUTMU AKU INI CANTIK?” Dewi bertanya lagi. Tangan ringkihnya menggenggam pergelangan Dimas yang basah kuyup oleh hujan.
Dimas menelan ludah. Perasaannya kocar-kacir tak karuan. Firasat buruk semakin mengguncang tiada henti. Akhirnya, ia mengangguk, mengiyakan.
“Apakah.. kau.. mau tau.. sese..orang yang aku cintai?” Dewi bertanya. Pertanyaan yang sama ketika waktu di metro.
Lagi-lagi Dimas hanya mampu mengangguk. Sudah tak kuasa ia berkata. Hatinya sedang menangis melihat orang yang sangat dicintainya sedang menahan sakit. Tanpa air mata hatinya meingkuk. Memilukan.
Kemudian pelan ia berkata sambil menunjuk ke suatu arah. Ke sebuah cermin yang menampakkan Dewi dan Dimas. “Yang., a..ku cintai.. adalah… A..” Kata-katanya terputus pada huruf A. “A..” Ia mencoba berkata. Menahan sakit yang diderma. Sakit seribu sakit. “Ak…”
Dan apa yang sedang diinginkan takdir langit malam tadi? Dewi pun kini sudah menghadap Sang kuasa. Ia tersenyum beku. Lesung pipinya terukir abadi. Bendera kuning berkibar. Perkuburan ramai. Dewi kini sudah dikebumikan. Orangtuanya menangis melepas kepergian anak semata wayangnya. Tapi, yang teramat sangat kehilangan adalah Dimas. Sampai sekarang pun ia tak tahu siapa orang yang dicintai Dewi. “AK…” Siapa ak itu. Tapi itu tidaklah penting. Sekarang tak ada lagi orang yang ia belai lembut rambutnya. Tak ada lagi orang yang selalu tersenyum padanya setiap pagi di metro. Tak ada lagi orang yang ia cubit pipinya. Pipi yang selalu membentuk teluk ketika tersenyum. Dewi sudah tiada. Dan sebelum meninggalkan Dimas sendirian di perkuburan yang sudah menyepi, orangtua Dewi menyerahkan sepucuk surat. Surat yang ditulis Dewi ketika masa-masa perjuangannya melawan kanker. Surat yang ditujukan kepadanya.
Kepada: Dimas Aksara
Dari: Dewi Andita
Hai, Dim. Mungkin tak sepantasnya aku bicara seperti ini. Maaf karena aku tak datang menepati janjiku untuk bertemu makan malam. Aku benar-benar tak menyangka tuhan tak akan mengijinkannya. Sebelum aku pergi, aku ingin mengungkapkan sesuatu yang aku pendam selama ini. Mungkin tak sepantasnya aku bicara ini. Kalau pun kau akan menerimanya, semuanya pasti akan terlambat. Tak berarti. Tapi, aku akan tetap mengungkapkannya. Dan dari hati aku yang paling dalam, aku merasa nyaman berada di dekatmu. Entahlah. Aku tak bisa menjelaskan rasa itu. Mungkin dengan tiga kata kau akan paham. AKU CINTA KAMU.
Ya. Aku sangat mencintaimu, Dim. Aku tau mungkin kau tak mempedulikanku. Kau hanya berusaha menanggapi apa yang aku lakukan. Tapi, yang kulakukan semua adalah karena aku mencintaimu, Dim. Sungguh. Apa kau tahu kenapa aku selalu ingin bersamamu ketika berangkat ke kampus? Itu karena aku ingin selalu bersamamu setiap pagi. Aku selalu kesepian, Dim. Orangtuaku tak mempedulikanku. Mereka hanya peduli pekerjaan mereka. Bahkan setelah aku divonis oleh dokter menderita kanker satu tahun yang lalu. Dan kau adalah satu-satunya penyemangat hidupku.
Apa kau tahu kenapa aku selalu menuding supir metro ketika hendak memberitahukan orang yang aku cintai. Apa kau tahu? Kau pasti mengira kalau aku menuding supir itu. Tidak, Dim. Aku tidak sedang menuding supir itu. Yang kutuding adalah cermin. Kaca spion metro yang lebar. Yang menampakkan wajahmu yang sendu. Ya. Itulah yang aku tunjuk. Dan itulah orang yang AKU CINTAI.
Terima kasih, Dim. Terima kasih telah menjadi penyemangat hidupku. Terima kasih sudah mewarnai hidup kelamku. Terima kasih. Kau benar-benar sepereti namamu. AKSARA. Kau memang seperti tulisan yang aku coretkan di setiap buku diaryku, hanya kaulah yang tahu apa yang aku coretkan itu
Salam Manis
Dewi Anandita
Dan setelah membaca surat itu. Badan Dimas mendadak menjadi kaku tak berdaya. Tak disangka ternyata orang yang amat sangat dicintainya ternyata juga mencintainya. Tapi, semua sudah terlambat. Ia kini sudah tiada. Dimas pun menangis. Berteriak parau. Menyesali dengan apa yang telah dilakukannya. Maka dengan penuh rasa bersalah ia belai nisan bertuliskan “Dewi Anandita” seperti halnya ia mengelus rambut “Dewi Anandita” ketika di metro…
Cerpen Karangan: Aris Fatah Yasin
Facebook: Aris Fatah Yasin
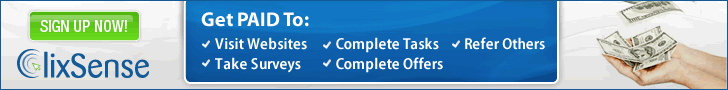
0 Comments